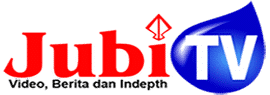Oleh : Deka Anwar
PEMBUAT kebijakan di Jakarta terus maju dengan rencana untuk membagi Papua menjadi empat provinsi meskipun ada perlawanan lokal yang kuat. Jakarta mengklaim ini akan mempercepat pembangunan dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat karena provinsi baru akan didasarkan pada kawasan budaya asli. Tetapi orang Papua melihatnya sebagai langkah untuk mengeksploitasi perpecahan politik regional alih-alih menangani pelanggaran hak asasi manusia dan marginalisasi orang asli Papua.
Pemerintah pusat telah lama mendorong pembagian Papua menjadi beberapa provinsi untuk menahan ancaman separatisme. Tetapi setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998, Jakarta tidak dalam posisi untuk menindaklanjuti hal ini. Pada tahun 2001, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang Otonomi Khusus untuk memadamkan permintaan referendum. Ditetapkan bahwa provinsi baru harus disetujui oleh pemerintah provinsi, termasuk Dewan Perwakila Rakyat Papua (DPRP).
Kemudian pada tahun 2003, mantan presiden Megawati Sukarnoputri membagi Papua menjadi Papua Barat dan provinsi Papua tanpa berkonsultasi dengan DPRP. Ini jelas melanggar hukum dan memperdalam ketidakpercayaan orang Papua terhadap Jakarta. Diskusi lebih lanjut tentang provinsi baru dihentikan setelah Lukas Enembe menjadi gubernur Papua pada 2013. Enembe memblokir petisi dari politisi lokal untuk membentuk provinsi Papua Utara dan Selatan karena akan mengurangi kekuasaan dan pendapatan Papua dari lokasi pertambangan yang kaya sumber daya.
View this post on Instagram
Pada tahun 2021, rencana untuk provinsi baru dihidupkan kembali setelah parlemen Indonesia mengesahkan undang-undang otonomi khusus yang direvisi, melucuti wewenang pemerintah Papua untuk menyetujui provinsi baru. Revisi ini terjadi meskipun ada protes keras dari banyak orang Papua sendiri, bertepatan dengan Enembe yang sakit dan kematian wakil gubernur Klemen Tinal. Pada bulan April 2022, parlemen memprakarsai proposal untuk empat provinsi baru — Papua Utara, Papua Pegunungan Tengah, Papua Tengah, dan Papua Selatan. (Dalam prosesnya kemudian menjadi tiga provinsi baru tanpa Papua Utara. Namun Papua utara muncul kembali setelah Gubernur Papua, Lukas Enembe mengusulkan Papua Utara sebagai provinsi baru kepada Mendagri Tito Karnavian – RED)
“Mengukir” Papua terutama menguntungkan pemerintah pusat di Jakarta dan elit pemerintah daerah. Jakarta dapat memberikan hibah dan proyek dengan lebih mudah dan bekerja sama dengan provinsi dan kabupaten yang lebih kecil untuk memantau pelaksanaannya. Unit administrasi baru juga akan membenarkan anggaran yang lebih besar bagi militer dan polisi untuk membangun lebih banyak pangkalan teritorial dan merekrut lebih banyak personel.
Elit lokal yang akan mengisi pemerintahan provinsi baru mengharapkan dividen dari proyek pemerintah dan investasi asing. Pendapatan dari proyek sub-daerah tidak lagi harus dibagi dengan daerah lain. Papua Tengah, yang akan memiliki enam kabupaten, akan menyimpan sebagian besar pendapatan dari tambang tembaga dan emas Freeport di Mimika dan tambang emas Blok Wabu di Intan Jaya senilai US$15,4 miliar. Elit lokal juga berkeinginan untuk mempercepat pembentukan provinsi baru agar bisa berpartisipasi dalam pemilu 2024.
Opini publik tentang provinsi-provinsi baru terbagi sepanjang garis patahan etnis-regional. Penentangan keras datang dari masyarakat di dataran tinggi tengah — wilayah pegunungan yang terbentang dari Kabupaten Nabire hingga Pegunungan Bintang. Daerah ini adalah kubu Enembe, mantan Bupati Puncak, dan di mana beberapa kekerasan paling mematikan sering terjadi.
View this post on Instagram
Sementara itu, masyarakat Papua yang tinggal di kabupaten-kabupaten pesisir telah lama mendambakan memiliki provinsi sendiri. Sejak pemerintahan kolonial Belanda, orang Papua dari kabupaten utara seperti Yapen, Biak dan Jayapura telah mendominasi politik provinsi. Tren bergeser ke dataran tinggi setelah Enembe memenangkan jabatan gubernur pada 2013. Politisi dataran tinggi juga mendapat manfaat dari sistem pemungutan suara noken, pemungutan suara tradisional dengan proxy, yang banyak dipraktikkan di dataran tinggi terpencil. Sistem ini seharusnya membantu mengatasi kekurangan infrastruktur, tetapi telah dikritik karena kurangnya transparansi dan kecurangan pemilih.
Pemisahan dari wilayah dataran tinggi akan memungkinkan politisi pesisir untuk merebut kembali pengaruh dengan memerintah Papua dengan ibu kota di Jayapura.
Yang terpenting, pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi baru tidak mungkin menyelesaikan masalah konflik kekerasan dan separatisme. Papua menghadapi berbagai masalah keamanan mulai dari pemberontakan bersenjata, ketegangan penduduk asli-migran, polarisasi intra-Papua, kekerasan pemilu dan konflik tanah.
Pemilu di Provinsi Papua telah lama diwarnai dengan kekerasan dan kecurangan pemilu. Menambahkan unit administrasi baru dapat meningkatkan ketegangan antara suku-suku tetangga yang sekarang bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan posisi di administrasi provinsi baru.
Orang Papua khawatir provinsi baru akan membuka pintu bagi pegawai negeri non-Papua yang mengisi birokrasi baru. Penduduk pendatang telah melampaui jumlah penduduk asli dan menempati posisi politik di kabupaten-kabupaten pesisir yang lebih berkembang. Pada Pemilu 2019, hanya 13 dari 40 kursi legislatif yang diraih oleh masyarakat asli Papua di Jayapura dan 3 dari 30 kursi di Merauke. Pada tahun yang sama, protes antirasisme di beberapa daerah berubah menjadi konflik komunal yang menyasar para pendatang.
Provinsi-provinsi baru sepertinya tidak akan mengekang pertumbuhan kekuatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Pemberontakan bersenjata kini telah meluas dari konsentrasi di empat menjadi sebelas kabupaten, termasuk di Maybrat, Papua Barat.
Meskipun mengunjungi Papua lebih dari para pendahulunya, kebijakan Presiden Indonesia Joko ‘Jokowi’ Widodo di Papua telah mengabaikan permintaan orang Papua untuk dimasukkan dalam pembuatan kebijakan. Alih-alih melibas jalannya untuk menciptakan provinsi-provinsi baru, Jakarta seharusnya terlibat dalam konsultasi yang berarti dengan rakyat Papua — atau berisiko memperkuat tuntutan kemerdekaan. (*)
Deka Anwar adalah Research Analyst di Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC)
Artikel ini diterjemahkan dari artikel pada Situs East Asia Forum berjudul The costs of carving up Papua