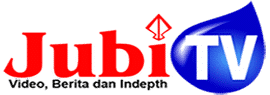Sentani, Jubi TV– Praktik perkawinan dini masih terjadi di Tanah Papua. Bagi masyarakat Papua di wilayah pegunungan, perempuan dianggap sebagai harta yang berharga, baik dalam keluarga maupun suku atau klan. Hal itu menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan dini.
Dokter Metty Wonda, seorang dokter perempuan asal Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah mengemukakan hal itu kepada Jubi, melalui telepon, Rabu (17/4/2024). Dokter Wonda mengabdikan diri sebagai dokter umum di Puskesmas Mulia Kabupaten Puncak Jaya.
Belum lama ini Dokter Wonda ikut membantu perjalanan dan proses persalinan seorang remaja perempuan berusia 14 tahun asal Kampung Bina, Kabupaten Puncak, dari RSUD Mulia ke RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura.
Menurut Dokter Wonda, perempuan dianggap sebagai berkat yang bisa menyelesaikan masalah keluarga atau suku tertentu ketika ada persoalan, seperti dalam konflik perang suku atau meringankan beban hidup dalam keluarga sehabis perang. Perempuan menjadi objek yang dapat diandalkan kapan saja, di mana saja, ketika situasi terdesak.
Dokter Wonda menjelaskan ketika terjadi konflik atau perang di kalangan suku tertentu, misalnya suku A mendapat bantuan dari suku B berperang melawan musuh bersama hingga perang selesai. Sehabis perang itu, Suku A berkewajiban memberikan penghormatan sebagai ucapan terima kasih berupa babi atau mengawinkan anak perempuannya, sekalipun masih kecil. Karena hal itu dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral dari suku A terhadap suku B.
“Kebiasaannya dong [mereka] habis perang to, kalau ada daerah lain yang bantu dong [mereka] ikut berperang, pasti setelah perang mereka kasih kawin sebagai tanda ucapan terima kasih bahwa mereka dibantu dalam perang. Jadi pasti dong [mereka] punya anak-anak perempuan kepala suku perang atau anak-anak dari daerah itu, kasih kawinkan dengan orang-orang yang bantu dong [mereka] dalam perang, seperti begitu,” kata dr Wonda yang berada di Mulia, Kabupaten Puncak.
Menurut dr. Wonda minimnya pemahaman dan pengetahuan orang tua di pedalaman Papua terhadap kesehatan reproduksi, usia bagi perempuan yang layak untuk kawin, mengandung dan melahirkan, menjadi persoalan utama.
Berdasarkan kebiasaan atau pengalaman masa lalu, lanjut dr Wonda, yang ada dalam benak orang tua ketika seorang anak perempuan sudah mulai tampak payudaranya membesar, itu diartikan telah bisa memiliki anak dan menyusui. Hal itu terjadi alami tanpa pengetahuan untuk mempertimbangkan usia, maupun kesehatan reproduksinya.
“Kebiasaan dari daerah itu, kalau anak perempuan sudah ada susu kelihatan begitu, mereka anggap perempuan itu sudah besar, bisa menyusui berarti bisa kawin, seperti [kasus] Desi Kula (14) itu begitu,” kata Wonda.
Sementara batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperbaharui dalam UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pada Pasal 1 bahwa perkawinan diizinkan apabila pria maupun wanita mencapai 19 tahun.
Sementara, menurut perspektif medis, lanjut dr Metty Wonda, seseorang dikatakan siap untuk kawin atau melahirkan keturunan mesti dilihat secara reproduksi, mental, dan psikologis. Bagi pria usia minimal 25 tahun, sedangkan perempuan sekurang-kurangnya mencapai 20 tahun.
“Untuk kawin atau menikah itu idealnya dari sisi kesehatan bagi laki-laki 25 tahun dan perempuan 20 tahun itu, baru dikatakan siap secara reproduksi, mental, dan psikologis. Jadi kalau laki-laki sudah mencapai usia tersebut, dia bertanggung jawab, begitupun perempuan 20 tahun itu [ketika] pikirannya dewasa, dan secara reproduksi juga dia sudah siap untuk membesarkan anak dalam kandungan apabila hamil dan melahirkan,” ujarnya.
Oleh karena, Dokter Metty yang juga bergabung dalam ‘Komunitas Medis Papua Tanpa Batas’ cabang Puncak Jaya. Ia bersama tim biasanya berkeliling ke kampung-kampung melakukan penyuluhan tentang risiko perkawinan dini. Selain itu juga melakukan penyuluhan tentang risiko seks bebas [seks beresiko dan tak aman] dan bahaya penyakit HIV/AIDS.
“Sekaligus memberikan pengetahuan dan informasi kepada orang tua, anak pemuda, remaja, dan juga gereja yang selama ini mereka belum tahu,” katanya.
Wonda menceritakan, pernah di suatu kampung di sela-sela penyuluhan itu, ia berdiskusi dengan beberapa orang tua di kampung tersebut. Ternyata ditemui bahwa salah satu penyebab perkawinan usia dini, karena kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuan terinfeksi penyakit HIV sehingga ketika mereka melihat anak perempuan atau laki-laki berpacaran atau melakukan pendekatan itu, orang tua langsung mengawinkan mereka.
“Saya tanya orang tua, kenapa anak masih kecil sudah dikawinkan? Mereka bilang, ‘kita sudah lihat dia jalan dengan laki-laki, jadi kita takut gonta-ganti laki-laki nanti dia kena penyakit [HIV]. Jadi begitu lihat kalau laki-laki siapa dekat dengan dia, kita langsung kasih kawin,” kata Wonda meniru jawaban orang tua.
Wonda meminta kepada Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, lembaga kesehatan, pihak gereja, lembaga-lembaga atau komunitas yang peduli persoalan perlu melihat krisis ini sebagai ancaman yang mesti diberi perhatian khusus melalui sosialisasi-sosialisasi atau penyuluhan.
Perkawinan usia dini tidak hanya terjadi di Puncak Jaya, tetapi sebagian besar masyarakat yang ada di pedalaman pegunungan Papua.
Mengutip rilis riset Wahana Visi Indonesia (WVI) pada 2021, terdapat 24,71 persen anak di Papua menikah di bawah umur 19 tahun. WVI bahkan mencatat ada anak yang menikah pada usia 10 tahun. Data dari riset tersebut dihimpun dari penelitian WVI di empat kabupaten dan kota, yakni Jayapura, Jayawijaya, Biak Numfor, dan Asmat.
Menurut Koordinator Program Manager Satgas Stunting Papua Mochamad Sodiq pada Oktober pada 2023, perkawinan dini menjadi salah satu variabel penyebab tingginya angka stunting di Kabupaten Supiori, Provinsi Papua.
Semasa masih menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise memprioritaskan program dan kampanye penghentian perkawinan anak usia dini. Fenomena yang angkanya cukup tinggi di Papua ini membuat Menteri Yembise, yang merupakan perempuan asli Papua, termasuk yang paling depan mengadvokasi revisi usia perkawinan dalam UU perkawinan menjadi minimal 19 tahun. (*)
Artikel ini sudah terbit di jubi.id