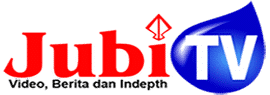Jayapura, Jubi TV – Pulang kampung atau yang dikenal dengan sebutan mudik sudah menjadi tradisi sejak lama bagi umat muslim di Indonesia, terutama mereka yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Tradisi ini terlahir dari mereka yang ingin merayakan Hari Raya Idulfitri atau berlebaran di kampung halaman setelah lama merantau.
Antropolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Heddy Shri Ahimsa Putra dalam sebuah tulisan di website resmi UGM mengungkapkan fenomena mudik mulai dikenal luas di Indonesia sejak 1970-an.
Menurutnya mudik berasal dari bahasa Melayu “udik” yang artinya ‘hulu’ atau ‘ujung’. Pada masa lampau, masyarakat Melayu yang tinggal di hulu sungai sering bepergian ke hilir menggunakan perahu atau biduk, lalu mereka akan pulang kembali ke hulu pada sore hari setelah urusan mereka selesai.
Sampai sekarang, mudik menjadi sebuah tradisi tahunan di Indonesia menjelang Hari Raya Lebaran. Mudik tak terlepas dari perkembangan pesat di kota-kota besar yang menimbulkan arus urbanisasi dari desa ke kota.
Di Papua, tradisi mudik hanya dilakukan sebagian orang yang datang merantau untuk bekerja. Mereka akan pulang ke kampung halaman setahun sekali atau beberapa tahun sekali.
Antropolog dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Hanro Yonathan Lekitoo mengatakan di Tanah Papua memang ada yang pulang kampung atau mudik, tapi tidak begitu masif seperti suasana mudik di Pulau Jawa dan Sumatera.
“Kalau saya melihat itu tergantung pilihan juga. Ada yang memutuskan pulang kampung dan ada juga yang tetap ingin bertahan dan merayakan di sini,” kata Hanro kepada Jubi, Selasa (9/4/2024).
Tidak demikian dengan sebagian orang yang lahir dan besar hingga memiliki keturunan di Papua. Seperti kelompok masyarakat transmigrasi yang sudah menetap di Papua hingga tiga generasi. Begitu pula dengan anak-anak dari para perantau yang lahir dan besar di Papua yang tak pernah tahu kampung halaman orang tua mereka.
“Ada yang sudah hidup dan menetap puluhan tahun, dua sampai tiga generasi di sini. Mungkin sebagian sudah tidak mengenal atau tidak tahu keluarga mereka di kampung halaman, mereka sudah menganggap di sini sebagai tanah kelahiran dan pemberi kehidupan,” kata Hanro.
Hanro menuturkan ketidaktahuan akan kampung halaman menjadi salah satu alasan bagi sebagian orang yang lahir dan besar di Papua tidak melakukan mudik.
“Anak cucu mereka yang lahir di sini mau pulang juga bingung mau cari siapa di kampung halaman orang tua mereka. Sudah hidup besar dan punya keturunan di sini, mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa mereka tidak mudik,” ujarnya.
Puluhan tahun tanpa pulang
Sudah puluhan lebaran Syamsudin tak pernah pulang ke kampung halaman. Pria berusia 68 tahun itu tak mengenal kata mudik selama puluhan tahun sejak ia hijrah dari Bone, Sulawesi Selatan, pada 1972. Syamsudin merantau ke Kota Jayapura, Papua saat masih berusia 16 tahun. Berbagai macam pekerjaan sudah digelutinya sejak pertama kali tiba di Tanah Papua.
Awalnya, ia merantau ke Jayapura ikut seorang kerabat dari kampung halamannya di Bone. Kebetulan, paman dari seorang kerabatnya itu sudah lebih dulu merantau ke Jayapura dan punya penghasilan yang lumayan dari hasil memulung limbah besi peninggalan perang.
Pada 1975, ia menikah dengan perempuan bersuku Jawa dan menetap di Batu Putih Atas, Polimak, lalu tinggal bersama teman perantau yang juga berasal dari Sulawesi Selatan. Setelah menikah, ia berpindah pekerjaan sebagai supir angkot wilayah trayek Sentani lalu berlanjut menjadi sopir angkot trayek Angkasa. Pekerjaan itu kemudian menjadi sumber mata pencahariannya hingga 2012.
Sejak 1970-an hingga awal 1990-an, setiap akhir bulan Ramadan, Syamsudin hanya bisa berkabar dengan sanak saudaranya lewat sepucuk surat yang dikirim melalui Kantor Pos. Namun, sudah lama ia mendengar kabar bahwa orang tuanya telah berpulang, begitupun dengan beberapa saudaranya.Karena alasan itulah, ia tak pernah pulang kampung.
Ketika Hari Raya Lebaran tiba, Syamsudin hanya merayakannya bersama keluarga besar dari sang istri yang kebetulan tinggal satu atap di tempat tinggal mereka yang sederhana di kawasan Batu Putih Atas.
“Setiap tahunnya kalau lebaran di rumah ini saja. Tidak pernah kemana-mana, apalagi pulang kampung. Mau pulang sudah tidak ada keluarga dan saudara,” kata Syamsudin bercerita kepada Jubi.
Hal ini juga turut dirasakan Sudir, pria 43 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai pengawas bangunan. Ia lahir di Jayapura pada 1981. Orang tua Sudir berasal dari Enrekang, Sulawesi Selatan dan sudah merantau ke Jayapura sejak 1978 dan meninggal dalam perantauan.
Sudir kini memiliki tiga anak dan tinggal di rumah peninggalan orang tuanya di Polimak. Ia tak pernah tahu di mana letak kampung halaman orang tuanya dan siapa keluarga besarnya di kampung. Puluhan tahun ia menetap dan melewati bulan Ramadan dan Hari Raya Lebaran di Jayapura.
“Dulu orang tua merantau ke sini sudah dari lama, orang tua juga meninggal di sini. Jadi tong ini mo pulang ke mana lagi? Tong pu rumah ada di sini,” kata Sudir.
Syamsudin dan Sudir bukan sedikit orang yang tak pernah merasakan mudik atau berlebaran di kampung leluhur. Warga transmigran di Arso, Kabupaten Keerom juga mengalami yang sama, seperti seorang pemuda bernama Irja.
Irja bekerja serabutan. Pagi hingga sore ia membantu temannya di bengkel, lalu malamnya ia menjadi sopir taksi online. Irja kini berusia 32 tahun kelahiran Arso.
Ia juga sama dengan pendatang lainnya yang lahir-besar di Papua, tak pernah merasakan pulang kampung atau mudik. Ketika Lebaran, ia hanya merayakan bersama orang tua dan keluarga kecilnya di Arso setiap tahunnya.
“Saya lahir besar di Arso mas, orang tua dulu merantau ikut transmigrasi. Jadi sampai sekarang kita belum pernah pulang kampung. Kalau lebaran, yah di sini saja,” kata Irja.
Tradisi lebaran
Sebagian orang-orang pendatang muslim yang sudah puluhan tahun tinggal di Jayapura dulunya punya tradisi khas setiap lebaran. Di Batu Putih Atas misalnya, warga muslim sehabis Salat Idulfitri dan syukuran sering berbagi makanan ke tetangga sekitar yang mayoritas Nasrani.
Tak hanya itu, umat muslim lama yang merayakan lebaran di Papua selalu membiarkan pintu rumahnya terbuka dan mempersilakan siapapun tamu yang datang untuk bersilaturahmi.
“Tradisi itu menarik sekali, jadi mereka yang sudah hidup lama di sini membangun hubungan yang baik sekali dengan tetangga di sekitar. Dan itu memang betul bahwa pada saat Hari Raya Lebaran semua pintu terbuka dan menyambut siapapun tamu yang datang. Begitupun tradisi membagikan makanan ke tetangga sehabis salat Idulfitri,” kata Antropolog Hanro Lekitoo.
Hanro yang lahir-besar di Teluk Wondama itu juga mengalami hal yang sama sewaktu kecil. Ia mengaku toleransi muslim dan Nasrani itu sudah terjalin erat sejak dulu.
“Saya ingat dulu itu ada teman orang tua asal Makassar, tinggalnya agak jauh dari tempat kami, tapi ketika dekat hari lebaran, keluarga saya jalan kaki hanya untuk berjabat tangan dengan mereka, begitu pula saat Natal mereka juga melakukan yang sama terhadap kami,” ujarnya.
“Toleransi itu terjalin sangat bagus di Papua dan telah terpupuk selama puluhan tahun. Meskipun agama berbeda, tapi kebersamaan itu tetap terjaga, karena setiap agama mengajarkan untuk saling mengasihi,” katanya.
Karena toleransi yang telah terpupuk selama puluhan tahun membuat perantauan muslim lama menganggap semua tetangga mereka adalah saudara dan memilih tetap merayakan lebaran tanpa harus pulang kampung.
“Makanya banyak pendatang yang sudah puluhan tahun hidup dan punya keturunan di sini itu tidak pulang kampung atau mudik. Mereka berpikir saudara mereka semua ada di sini,” kata Hanro. (*)
Artikel ini sudah terbit di jubi.id