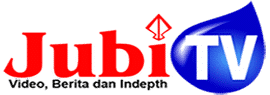Jubi TV-Indonesia mungkin memiliki peringkat yang lebih baik dalam indeks demokrasi dibandingkan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, tetapi dalam kenyataannya, hal tersebut tidak dirasakan demikian bagi para aktivis di Papua. Fakta menunjukan, mereka yang berjuang mendukung Papua merdeka, yang berseberangan dengan pemerintah Jakarta, sering ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara.
Papua Barat saat ini menjadi bagian wilayah Indonesia melalui sebuah pertempuran dan sejarah yang kontroversial. Menurut Indonesia, rakyat Papua Barat telah memilih untuk hidup di bawah pemerintah Indonesia melalui referendum yang dikenal dengan “Act of Free Choice” atau Pepera pada 1969. Kurang dari satu persen penduduk Papua telah memberikan suaranya pada referendum tersebut, dan sebagian besar orang Papua pada kenyataannya tidak punya pilihan sama sekali.
Para aktivis pro-kemerdekaan Papua menghadapi resiko-resiko serius: penyiksaan yang kejam setelah penangkapan itu sudah umum. Mereka juga menghadapi tantangan-tantangan lain bila dipenjarakan, seperti bagaimana untuk tetap optimis dan menjaga komitmen perjuangan mereka.
Empat mantan tahanan politik Papua – Jefri Wandikbo, Agus Kraar, Filep Karma dan Linus Hiluka — mengungkapkan kepada penulis bahwa penjara itu tidak akan mengakhiri perjuangan. Sebalikya, penjara itu hanyalah sebuah awal.
Kisah mereka terbagi dalam empat bagian: penangkapan, interogasi, penjara dan kehidupan sesudah penjara.
Penangkapan

Pada 4 April 2003, gudang senjata Komando Distrik Militer 1702 di Jayawijaya, Wamena, diduga dirusak oleh para aktivis politik yang mengambil senjata. Selama satu bulan, aparat militer menyisir wilayah Jayawijaya, memburu para pelaku yang dikenal dengan “Kasus Kodim 1702”. Mereka menangkap Linus Hiel Hiluka, yang menjadi bagian dari operasi pembobolan gudang senjata.
Linus lahir di Kampung Ibele, Kabupaten Jayawijaya pada 25 Agustus 1974, dari orang tua yang bekerja sebagai petani. Sebagai orang muda terdidik, Linus awalnya dikenal sebagai aktivis gereja. Pada 1999, dia berpartisipasi dalam pertemuan yang digelar oleh Forum Reskonsiliasi Rakyat Irian Jaya (FORERI), sebuah organisasi pro-kemerdekaan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh sipil Papua.
Pada tahun yang sama, ia menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) yang merekomendasikan diadakannya Kongres Rakyat Papua Kedua yang mengeluarkan resolusi “Kemerdekaan Papua sebagai bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961”, dan menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua Barat. Kongres itu juga mendukung 31 anggota Presidium Dewan Papua (PDP)—sebuah kelompok yang dibentuk untuk mewakili kampanye kemerdekaan Papua Barat—dan memilih Theys Eluay sebagai ketua.
Satu tahun kemudian pada 2001, Theys, yang dikenal sebagai “Pemimpin Besar Rakyat Papua”, dibunuh oleh Kopassus dan ditemukan tewas. Tujuh dari anggota pasukan khusus Indonesia itu bahkan telah dihukum dan dipenjara antara enam bulan hingga maksimum tiga tahun. Dalam pandangan militer mengenai aktivis pro-kemerdekaan di Papua, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Ryamizard Ryacudu – yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan Indonesia—menyebut para tentara itu sebagai “pahlawan”.
Pada 23 Maret 2000, Linus mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan halaman rumahnya. Bendera Bintang Kejora merupakan simbol kontroversial di Papua Barat—telah dilarang sejak 1969. Walaupun larangan ini sempat melunak seiring diizinkannya pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai identitas budaya (selama bendera Indonesia bisa dikibarkan lebih tinggi dari bendera Bintang Kejora), bendera itu kembali dilarang karena dianggap ‘separatis’.
Aparat keamanan di Papua terus menggunakan pelarangan ini sebagai alasan memenjarakan orang-orang yang mengibarkan bendera itu karena dianggap pengkhianat (negara).
Keputusan Linus mengibarkan bendera merupakan sikap politik yang berani sehingga ia dikenal sebagai aktivis pro-kemerdekaan di distriknya. Sejak saat itu, masyarakat memandang ia menyuarakan perjuangan politik untuk kebebasan.
Tiga tahun sesudah Linus menghadiri Kongres Rakyat Papua Kedua, aparat keamanan menduga kuat bahwa kasus Kodim 1702 dilakukan oleh kelompok yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), payung organisasi gerakan kemerdekaan di Papua Barat. Aparat keamanan menyisir kampung-kampung di sekitar Wamena dan menangkap sejumlah orang, termasuk Linus.
Mereka dituduh terlibat dalam penyerangan gudang senjata. Karena Linus terlibat dalam Kongres, pihak berwenang mengklaim bahwa dia mengetahui aksi-aksi OPM tersebut.
Anggota Komando Strategis Angkatan Darat, atau Kostrad, mendatangi rumahnya pada pagi hari, Linus menjelaskan dalam sebuah wawancara telepon dengan penulis. Para tentara itu tak ragu-ragu menembak.
“Mereka tembak jendela ke dalam, ada tembakan rentetan senjata, barulah saya bangun. Ibu saya dan keluarga semua juga bangun. Saya mau keluar tetapi keluarga tahan saya. Kalau saya lari nanti sasarannya masyarakat Maka, saya keluar. Itu masih gelap. Pasukan dengan menyorotkan cahaya senter menangkap saya,” kata Linus. Ia ditangkap sekitar pukul 04.30.
“Lalu masyarakat kumpul di halaman, termasuk bapa gembala (pendeta) disuruh tiarap. Aparat masih melakukan penembakan hingga jam enam pagi. Rumah saya digeledah, mencari barang-barang atau senjata-senjata dari gudang Kodim, tetapi mereka hanya menemukan bendera Bintang Kejora, dokumen-dokumen perjuangan, yang lain tidak dapat.”
Sesudah ditemukan bendera Bintang Kejora di rumahnya, Linus diborgol, dijemput oleh badan intelijen negara dan dipindahkan ke pusat komando distrik militer. Dia dinterogasi dan dituduh menyembunyikan peluru dan senjata yang diambil saat penyerangan di gudang senjata. Tetapi Linus bersikeras bahwa dia tidak terlibat— sebuah keyakinan yang dia pertahankan hingga hari ini.
Jefri Wandikbo, seorang aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebuah organisasi non-kekerasan yang mengkampanyekan referendum bagi penentuan nasib sendiri, mengatakan kepada penulis bahwa pasukan keamanan kadang-kadang melakukan penyergapan tiba-tiba saat menangkap para aktivis.
Pada 7 Juni 2008, Jefri berada di taksi bersama ketua KNPB Buchtar Tabuni, dan Assa Alua, saat itu mereka menyadari sedang diikuti. Polisi sedang menunggu, dengan senjata lengkap, ketika mereka tiba di Abepura. Mereka tidak punya pilihan lain selain menyerah. Mereka dibawa ke Kepolisian Daerah Papua.
“Kami digeledah, barang-barang kami digeledah, semua diperiksa. Tas saya, kamera, buku catatan saya, itu diangkat semua, termasuk beberapa flashdisk,” kata Jefri.
Merunut ke belakang, Jefri meyakini mereka telah dijebak. Situasi di Papua Barat saat itu tegang; KNPB telah memimpin sejumlah demonstrasi menuntut referendum di sejumlah daerah.
Meningkatnya konflik dan diikuti kekerasan, terjadi penembakan di beberapa tempat—kejadian yang umum di Papua Barat dimana kekerasan diprovokasi oleh aktor-aktor yang tidak dikenal, mengubah demonstrasi damai menjadi situasi kacau. Puncaknya penembakan seorang warga negara Jerman di Pantai Base G di Sentani, Jayapura.
Pelaku penembakan itu tak pernah ditemukan, tetapi pihak berwenang menuduh KNPB. Dewan Perwakilan Rakyat Papua menyurati KNPB, mengundang mereka dalam sebuah pertemuan yang membahas penembakan itu. Juga diundang Pangdam Cenderawasih, Kapolda, dan sejumlah LSM. Buchtar Tabuni mewakili KNPB hadir, tetapi Pangdam dan Kapolda tidak muncul. Pertemuan itu ditunda hingga minggu berikutnya.
“Saya dan Assa Alua mendampingi Buchtar Tabuni segera pulang karena rapat dibatalkan. Rupanya itu diciptakan untuk menangkap kami,” kata Jefri.

Gustaf Kawer, seorang pengacara hak asasi manusia yang mendampingi Jefri, mengatakan ada pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus-kasus yang dialami anggota KNPB. “Polisi sudah menghambat [akses mereka pada keadilan] dengan menangkap, menyiksa, menahan tanpa prosedur yang jelas,” kata Gustaf kepada penulis melalui telepon.
“Saat proses penangkapan itu di undang-undang juga diatur, tentang bagaimana para aktivis ini punya hak-hak mendapat pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga, hak untuk perawatan kesehatan, mendapat kunjungan rohaniawan. Nah semua ini ditutup,” kata Gustaf.
Para aktivis itu diinterogasi tanpa didampingi pengacara. “Waktu interogasi, sesuai dengan KUHAP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara, itu harus didampingi pengacara kalau ancaman hukumannya di atas lima tahun. Kalau yang bersangkutan tak mampu mencari pengacara, polisi wajib menunjuk pengacara. Nah, ini kan tidak,” jelas Gustaf.
“Saat pemeriksaan, polisi sudah memeras pengakuan mereka, baru ruang itu dibuka setelah ada komplain pengacara. Dalam proses pemeriksaan acara, penahanan sebenarnya bisa singkat tapi dibuat lama, berbulan-bulan hingga mau habis masa penahanannya. Lalu dilimpahkan ke kejaksaan. Di sana juga panjang prosesnya. Sampai di persidangan sebenarnya ada yang tidak terbukti tapi kemudian mereka divonis bersalah juga,” ujar Gustaf.
Menurut Gustaf, polisi memaksakan pengakuan melalui penyiksaan, pemukulan dan bermacam-macam bentuk lainnya. Bagi Linus, itu bukan mengada-ada; ia mengalaminya sendiri saat dirinya ditangkap.
“Jam 9 pagi, saya masuk di ruangan interogasi khusus Kodim. Saya diinterogasi dari jam 9 pagi itu terus…. sampai jam 12 malam. Saya disuruh duduk, disiram air dari atas hingga lantai tergenang air, lalu ditanya, diinterogasi. Cara interogasi itu penyiksaan yang bagus punya. Saya disiksa, dipukul dengan popor senjata.”
Kepala distrik Wamena dan beberapa pendeta mendesak militer agar memindahkan Linus ke Kepolisian Resor [Polres]. Tetapi ketika dia tiba di kantor polisi, dia mengatakan Kapolres menolak untuk membawa masuk ke tahanan karena kondisinya buruk.
Kapolres khawatir bahwa kasusnya akan mendapat sorotan, dan hanya menerimanya setelah dokter melakukan pemeriksaan kesehatan lengkap untuk menjelaskan kondisinya yang memburuk. Linus bolak-balik beberapa kali ke kantor polisi dan rumah sakit.
“Satu minggu kemudian, saya diperiksa. Kemudian saya dilimpahkan ke ‘Lembaga’ (sebuah penjara lama di Wamena). Saya dimasukan ke satu ruangan. Itu ruangan sejak jaman Belanda. Ruangan itu gelap sekali, tidak ada cahaya. Ruangan kecil. WC segala macam itu satu tempat. Itu tempat kondisi yang paling buruk. Saya tinggal selama satu bulan di ruang itu. Kemudian, saya dipenjara dalam penjara biasa. Penyiksaan di LP itu tetap saya dapatkan.”
Linus mengatakan ia menerima “penyiksaan halus”, praktik-praktik diskriminasi yang digunakan terhadap beberapa tahanan, seperti memberikan mereka makanan yang kualitasnya buruk dan kekerasan secara verbal.
Setelah polisi melengkapi laporan pemeriksaan mereka, kasus Linus dilimpahkan ke kejaksaan. Dia didakwa dan dihukum karena pengkhianatan dan konspirasi, dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.
Jefri juga mengatakan dia mengalami kekerasan dan penyiksaan. Dia, Buchtar dan Assa diinterogasi semua. Assa kemudian dibebaskan, tetapi Jefri dipindahkan ke sel isolasi di Kepolisan Resor Kota Jayapura. Buchtar tetap di Kepolisian Daerah Papua.
“Sekitar satu bulan, saya di sel isolasi. Saya tidur di lantai, tidak pakai alas sama sekali. Saya sering sakit, pokoknya badan ini dingin semua, sakit sekali,” kata Jefri.
Ia kemudian dipindahkan ke sel yang berbeda, tetapi masih belum dihukum karena pelanggaran apa pun. Ia dilarang berkomunikasi dengan sesama narapidana, meskipun ia telah bertemu dengan teman KNPB lainnya yang juga ditangkap dan ditahan.
“Saya kembali diperiksa, di-BAP di sana. Mereka menyuruh atau memaksa saya untuk mengaku, ‘penembakan-penembakan itu kamu yang melakukan’. Kami memang tidak melakukan, jadi kami bertahan,” kata Jefri.
Jefri mengatakan bahwa, selama ia diinterogasi, dia ditelanjangi. Tangannya diikat pada kursi, dan mereka menggunakan batang sapu untuk menekan keras kemaluannya. “Itu sakit sekali, waktu itu tidak baik, sampai saya berteriak,” kata Jefri.
“Mereka melakukan supaya ‘itu kita yang melakukan, begitu’. Akhirnya BAP itu dibuat seakan-akan kita yang mengaku, mereka buat BAP itu semau mereka. Walaupun saya tidak bicara, mereka masukan semua supaya saya kena pasal,” kata Jefri lagi.
Suatu malam, dia dibawa keluar dari penjara. “Mereka bungkus kepala saya dengan plastik hitam, lalu seseorang ada yang bilang ‘ah sudah buang saja ke laut untuk makanan ikan.’ Itu untuk mengganggu psikologis saya. ‘Sudah ditembak saja’. Saya ditodong senjata,” kata Jefri.
Jefri didakwa dengan pasal berlapis, termasuk kepemilikan tulang kasuari di dalam tasnya. (Tulang Kasuari dipakai alat tradisional di Papua dan dianggap senjata tajam oleh polisi.) Dia divonis hukuman penjara 10 bulan untuk itu. Ia juga dituduh terlibat pembunuhan sopir ojek motor di Waena, Jayapura, pada 22 Mei 2012.
Padahal ia punya bantahan—ia sedang mengunjungi orang tuanya di Wamena, daerah pegunungan di Kabupaten Jayawijaya pada waktu itu—ia dipidana dan dihukum delapan tahun penjara. Upaya bandingnya ditolak.
Namun penangkapan-penangkapan itu sering kali gagal meredam suara lantang aktivis politik di Papua. Bagi para pemuda Papua, penjara tidak lagi menghantui atau menakutkan. Bahkan, terkadang sebaliknya, seolah-olah penangkapan ribuan aktivis sesungguhnya telah memupuk keberanian banyak anak muda dan aktivis perjuangan Papua.
Di Penjara

Agus Kraar, mantan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua, telah dua kali di penjara — pertama selama 20 hari, lalu tiga tahun. Dia kali pertama ditangkap saat ambil bagian pada pengibaran bendera ketika memperingati perayaan proklamasi Kemerdekaan Melanesia di Papua Barat. Dia dibebaskan kurang dari satu bulan, pihak berwenang menemukan bahwa dia hanya menghadiri acara itu tanpa ada keterlibatan lainnya.
Dia ditangkap untuk kedua kalinya pada Kongres Rakyat Papua Ketiga di Abepura pada 2011. Ia dan empat tahanan lainnya dituduh melakukan pengkhianatan dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.
Seperti aktivis lainnya, Agus mengatakan kepada penulis bahwa penjara tidak menghalanginya untuk memperjuangkan keadilan bagi rakyat Papua. Bahkan, pengalaman itu mengajarinya bukan hanya mengenai kehidupan penjara, tetapi juga dunia.
“Setelah saya dipenjara, saya tahu banyak orang yang tidak bersalah tapi masuk penjara. Bukan saja tahanan politik tapi juga korupsi atau pembunuhan. Setelah tiga tahun di penjara, saya melihat banyak hal terjadi. Penjara membentuk kita dan hal-hal tidak baik (tentang diri kita sendiri) kita kurangi,” jelas Agus.
“Terutama bagi kita pejuang kemerdekaan, memang penjara itu satu-satunya tempat yang menunggu kita. Kita tetap berjuang tapi akhirnya kita masuk dalam penjara. Karena tidak ada tempat lain (bagi kita). Hanya ada dua hal. Pertama, dibunuh. Kedua, masuk dalam penjara,” kata Agus.
“Penjara tidak akan membatasi kami atau memberikan efek jera. Kami akan berjuang,” kata Agus menambakan. “Kalau berhasil kami akan menikmati kemerdekaan, tapi kalau kami mati berarti perjuangan itu tidak mati, akan hidup dari generasi ke generasi.”
Linus dikurung di penjara Wamena selama sekitar satu tahun, setelah itu ia dan lima tahanan politik lainnya tiba-tiba dipindahkan — tanpa pemberitahuan kepada anggota keluarga sekalipun — ke sebuah penjara dengan keamanan maksimum di Makassar, Sulawesi, selama tiga tahun. Ia mengatakan dipukuli dan dilecehkan saat pemindahan itu.
Lima dari mereka dipindahkan kembali pada Januari 2008 setelah tekanan kuat dari teman-teman dan keluarga yang takut akan keselamatan mereka; tahanan keenam tewas saat di penjara. Terlepas dari protes yang menyebabkan mereka kembali ke Papua, Linus mengatakan dia terus mengalami penyiksaan dan kekerasan. Dia menjalani hukuman penjara selama tujuh tahun sebelum Presiden Joko “Jokowi” Widodo memberinya grasi pada 2015.
Namun, Agus memiliki pengalaman yang jauh lebih baik di penjara. “Ketika saya pertama kali masuk penjara Abepura, orang mengatakan saya dipukul, dianiaya. Itu perkenalan di penjara. Ternyata tidak untuk tahanan politik, kecuali orang yang memerkosa atau mencuri. Sekarang saya lihat pendekatan berbeda. Sekarang tidak ada yang dipukul, dibunuh. Sekarang tidak seram.”
Agus bisa membuat kebun di dalam penjara. Dia menanam singkong, pepaya, kol, dan memberikannya kepada para pengunjung. “Mereka senang. Kunjungan berikutnya mereka membawa baju, buku-buku, odol, sabun, indomie. Orang-orang di luar sana membantu,” katanya.
Sebuah Penahanan Panjang
Bagaimana tahanan politik yang tetap berada di balik jeruji selama lebih dari satu dekade? Bagaimana seseorang bertahan dan tetap menjaga perjuangan?
Filep Karma, yang digambarkan sebagai “tahanan politik paling terkenal di Papua Barat”, adalah salah salah satunya. Ia dihukum karena pengkhianatan dan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun pada 2005 dan perayaan pada 2004 terlibat dalam pengibaran bendera Bintang Kejora. Ia berbicara kepada New Naratif di Penjara Abepura, Jayapura pada Juni 2015. Ia berusia 55 tahun pada saat itu dan telah dipenjara selama lebih dari 10 tahun. Ia telah dibebaskan.
Dikagumi dan dihormati, Filep dikenal di dalam penjara karena penampilannya yang unik: ia sering mengenakan pakaian coklat, seperti seragam pegawai negeri, dengan sebuah tanda pengenal – sepotong kertas seukuran kartu identitas bergambar bendera Bintang Kejora menempel di dada.
“Saya masak sendiri, dengan kompor dari kaleng susu kental yang dilubangi. Masaknya pakai kaleng biskuit Khong Guan, dipotong setengah, sudah jadi kayak kompor, atasnya dikasih rantang stainless,” kata Filep pada 2015, menceritakan rutinitasnya di penjara.
Ia memasak makanannya sendiri, mengambil sayuran dari kebunnya sendiri. Ia menanam daun gedi dan singkong. Filep suka makan sayuran rebus, tanpa garam. Jika dia ingin penyedap, dia mencampurnya dengan mie instan. “Saya makan seperti itu setiap hari,” katanya
Keluarga dan teman-teman yang mengunjungi akan membawa makanan yang lebih enak. “Mereka bawakan ikan, wam (daging babi)…. Pernah juga dibawakan daging buaya… enak rasanya.”
Hari Natal adalah hari istimewa.
Filep merayakan Natal bersama teman-temannya dengan acara bakar batu, sebuah tradisi penduduk yang tinggal di pegunungan, memasak daging dengan dimasukan ke dalam batu yang telah dibakar. Daging itu diberikan bumbu dan dicampur sayur dari daun-daunan mentah. “Saya senang bisa bikin kegiatan di sini seperti di luar. Saya melihat orang lain senang, saya senang. Saya bisa membuat orang lain senyum, saya bergembira.” kata Filep.
Berkebun, memasak dan menonton televisi — bagi Filep, aktivitas-aktivitas itu membantunya menghadapi hidup di dalam batas-batas dinding penjara. Kembali pada tahun 2015, Filep mengungkapkan rahasia tetap sehat ketika di dalam penjara: triknya adalah mengubah pemikirannya, dan melihat penjara sebagai sebuah rumah.
“Jangan berpikir ini penjara. Kalau berpikir ini penjara kamu tersiksa. Saya bilang, lama-lama pindah ke sebelah, di sebelah rumah sakit jiwa. Jadi harus berpikir di rumah sehingga at home. Kamarnya dibersihkan, didekorasi sesuai selera sehingga nyaman,” kata Filep.
Filep aktif dan kreatif di penjara. Ia dan rekan-rekannya pernah mengadakan pelatihan membuat bingkai foto dengan kertas daur ulang — bingkai yang menarik kemudian dijual ke pengunjung. Ia juga menjual Tabloid Jubi, surat kabar independen yang didirikan oleh organisasi masyarakat sipil, setiap kali edisi baru keluar. Dia berharap teman-temannya di penjara tetap mengikuti berita-berita di Papua.
Di atas semua itu, Filep menawarkan sesuatu yang tidak terduga: pelatihan tinju. Pelatihan itu diadakan atas persetujuan pimpinan penjara. Bahkan arena tinju dibangun. Ia merasa penting untuk melibatkan narapidana yang lebih muda: ketika ia dikirim ke penjara, ia mengatakan, ada sekitar belasan aktivis di balik jeruji bersamanya. Sebagian besar dari mereka punya potensi dan talenta, tetapi tidak dilatih.
Selain tahanan politik, ada juga narapidana yang dihukum karena kejahatan lain. “Saya motivasi adik-adik yang kena kasus kriminal, jangan balik lagi ke sini,” kata Filep.
Jefri adalah salah satu aktivis muda yang berada di bawah sayap Filep. Pada 2014, ia mengikuti kejuaraan tinju daerah di Sarmi, delapan jam dari penjara. Ia memenangkan medali perunggu; narapidana lain meraih perak dan emas. “Bapak Filep melihat anak-anak yang masuk di dalam penjara ini punya potensi bagus, namun tidak ada kegiatan di dalam penjara. Arena tinju dibuat agar kelak sesudah keluar penjara bisa diterima oleh masyarakat,” kata Jefri.
“Dia tahu pelatih-pelatih tahun 1980 dan 1990an. Dia punya keluarga, akhirnya diundang untuk melobi dan minta persetujuan ke Kementerian Hukum dan HAM. Akhirnya diizinkan mendatangkan pelatih dari luar, yang didatangkan dari Jayapura,” kata Jefri lagi.
Pekerjaan penjara
Jefri telah dipenjara selama lebih dari setahun ketika ia dipercaya sebagai asisten keamanan untuk membantu menjaga ketertiban. Ia mulai menjadi anggota biasa tim keamanan, tetapi dipromosikan memimpin tim setelah pembebasan rekannya. Tugasnya sehari-hari menemani penjaga penjara ketika mereka membuka atau mengunci blok setiap hari.
Ia juga diberi pekerjaan lain: ia mengetik surat yang dikirim ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta dokumen administrasi seperti daftar kehadiran dan tahanan.
Ia bersedia untuk mengambil peran ini, tetapi katanya ia tetap seorang aktivis yang menolak menyerah. Ia membenarkan pekerjaan itu sebagai cara untuk tidak menyia-nyiakan waktunya di penjara.
Namun tak peduli seberapa banyak pekerjaan yang ia dimiliki, kesepian, kata Jefri, adalah bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan penjara. Ketika dilanda rasa sepi, ia akan memetik gitar dan menyanyi.
Kehidupan setelah penjara

dan Linus Hiluka/Basilius
Seminggu setelah ia dibebaskan dari penjara pada 27 Juli 2014, Agus terbang ke Biak, sebuah pulau kecil di pantai utara Papua. Ia memutuskan kembali tinggal di kampung halamannya.
“Saya senang bertemu sanak saudara. Banyak yang datang ke rumah untuk bertemu. Jabat tangan, berpelukan, melepas rindu,” kata Agus.
“Hidup saya kembali seperti biasa. Sehari-hari pergi ke kebun, mencari ikan di laut. Saya berenang di laut lepas Samudera Pasifik. Ada ombak pecah saya lewati, berenang, menikmati ciptaan Tuhan.”
Ia saat ini berusia 54 tahun. Ia telah mengabdikan separuh hidupnya untuk perjuangan Papua merdeka. Saat ini ia melihat sisi lain dari kehidupannya.
“Kalau tidak saya cari Tuhan, hidup saya di dunia ini akan sia-sia,” kata Agus. “Sejak saya keluar dari penjara, tugas utama saya mencari Tuhan. Ibadah di gereja saya hadir. Ibadah di keluarga saya hadir.”
Namun itu bukan berarti ia menyerah. Sebaliknya, Agus melihat perannya punya pengaruh; ia sekarang bekerja menyatukan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik, baik itu kelompok pro-kemerdekaan maupun pro-Indonesia. Ia juga menyediakan ruang di rumahnya untuk para pemuda Papua dari pegunungan untuk belajar dan menjadi aktivis.
Filep bebas dari penjara Abepura pada 19 November 2015. Sejak itu ia sering melakukan perjalanan. Sesudah merayakan Natal untuk pertama kalinya bersama keluarga setelah lebih dari 10 tahun, ia pergi ke Jakarta pada 2016, mengikuti pelatihan, pertemuan mahasiswa dari Jawa dan Bali, dan berbicara dengan para aktivis hak asasi manusia dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Ia juga mengunjungi kota Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Malang.
Meski secara resmi pensiun dari pekerjaan pada September 2017, Filep terus bergerak. Dia pergi ke Jenewa pada 2017 untuk ambil bagian dalam sidang Universal Periodic Review di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Ia juga mengunjungi beberapa negara di Eropa untuk berbicara masalah hak asasi manusia di Papua Barat, dan bertemu dengan para siswa di Jerman yang mengirim kartu pos saat ia di penjara.
Linus kembali bertani dan bekerja di kebun. Ia menanam dan menjual singkong, kangkung, pisang, ubi jalar untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Ia bertekad enam anaknya bisa menjadi sarjana.
“Kehidupan kami sekian tahun sudah hancur. Sumber-sumber pendapatan dari hasil-hasil bumi sudah hancur. Jadi mau pulihkan ini lama,” kata Linus.
Itu bukan satu-satunya baginya untuk memulihkan: masalah kesehatan yang ia derita akibat penyiksaan ketika di penjara. Ia menolak tawaran bantuan keuangan dari pemerintahan Jokowi karena mereka datang dengan syarat-syarat: ia diminta berjanji setia kepada Republik Indonesia.
“Kami ini tokoh politik, dan kami masuk karena kasus politik perjuangan Papua merdeka. Maka masuk dan keluar penjara harus selesaikan politik. Selesaikan perjuangan. Kami akan kembali ke habitat, tugas kami ke masyarakat. Maka, kami tidak tandatangani syarat-syarat apapun,” kata Linus.
Jefri sekarang merintis usaha kecil untuk menopang ekonominya. Ia memiliki kios yang menjual aneka barang kebutuhan sehari-hari dan sedang berjuang menyelesaikan pembangunan empat kios lainnya. Ia percaya bahwa aktivis seharusnya fokus membangun fondasi keuangan yang kuat, perjuangan itu tidak hidup dalam kekosongan. “Ekonomi aktivis itu harus kuat dulu, misalnya, punya isteri dan anak harus kasih makan, cari makan,” katanya.
“Saya pikir tidak harus pikir politik, tapi juga gerakan ekonomi. Seperti kita harus punya usaha, seperti kios, berkebun, ojek. Yang penting ada pendapatan setiap hari,” kata Jefri.
Ini sikap yang sangat praktis, mungkin memberi kesan seorang aktivis yang mundur dari kehidupan masyarakat. Namun anggapan itu salah. Bagi tahanan politik Papua, tidak perlu berhenti berjuang; mereka bisa saja mengembangkan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. (*)
Basilius Triharyanto adalah seorang penulis dan editor. Ia telah menulis dan mengedit sejumlah buku terkait hak asasi manusia, sejarah, dan masalah sosial.
*) Naskah ini pertama terbit di media New Naratif pada 2018. Laporan ini dipublikasikan kembali untuk mengenang wafatnya Filep Karma, salah satu tokoh dan narasumber dalam laporan jurnalistik ini.