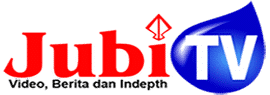Jubi TV – “Dari timur ke timur”, kalimat ini pas untuk menggambarkan perjuangan dari anak-anak anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka yang memilih melanjutkan perjuangan orang tua mereka. Bagi mereka, cita-cita untuk memerdekakan Papua selalu ada. Begitu pula dengan anak-anak dari para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua.
Demianus Magai Yogi, salah seorang anak tokoh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM) di Kabupaten Paniai, Tadeus Yogi, memilih mengikuti jejak ayahnya untuk mengangkat senjata. Ia kini menjadi kombatan TPNPB karena menyaksikan keluarganya menjadi korban kekerasan oleh aparat TNI/Polri.
“Bapak kandung saya, Panglima Tinggi Tadeus Magai Yogi memimpin pergerakan kemerdekaan bangsa Papua sejak awal tahun 1970-an, hingga beliau menghembuskan nafas terakahirnya pada 9 Januari 2009,” kata kata Demianus.
Demianus mengatakan kehidupan yang aman dan damai adalah sesuatu yang mustahil bagi seorang anak tokoh TPNPB. Ia menerimanya sebagai konsekuensi dari perjuangan orangtuanya.
“Kami hidup tidak terlepas dari teror dan intimidasi kepada Tadeus Yogi, istrinya, dan anak-anaknya. Bahkan Tadeus Magai Yogi meninggal dunia akibat diracuni. Kalau mama, meninggal karena sakit, kelelahan kerap dikejar aparat,” kata Demianus sambil mengenang kedua orang terkasihnya.
Egianus Kogoya, memilih jalan yang sama dengan ayahnya, Silas Kogoya
Kendati ayahnya telah meninggal, Demianus menuturkan ia dan saudara-saudaranya terus mengalami intimidasi, teror, dan diincar timah panas aparat keamanan. Sejumlah tujuh orang saudaranya meninggal dalam konflik panjang yang terjadi di sekitar Kabupaten Paniai.
“Kaka, dan adik saya ada sekitar 7 orang yang meninggal dunia. Seperti Antonius M Yogi, dibius oleh aparat di sekitar Ugi, Distrik Panitiai Timur, pada tahun 2017 silam. Yosina M Yogi ditembak oleh pasukan TNI/Polri di Pugo, Paniai. Salmon Magai Yogi ditembak oleh pasukan TNI/Polri di Markas Komando Daerah Pertahanan TPNPB Paniai di Eduda pada 2013. Leo M Yogi diembak TNI/POLRI di Nabire pada tahun 2015 silam. Kristianus M Yogi ditembak Tim Kasuari di Ugapuga pada tahun 1997. Paul M Yogi meninggal dunia di Markas Eduda pada tahun 2002. Debora M Yogi meninggal dunia di Markas Eduda pada tahun 2005 silam,” katanya.
Demianus menyatakan orang-orang yang terlibat membunuh saudaranya tidak pernah diadili dan dihukum. Sama seperti para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua yang juga tidak pernah diadili dan dihukum. “Tidak hanya adik dan kakak saya, hampir sebagian anak-anak OPM selalu mendapatkan perlakukan demikian, kalau tidak disiksa, dibunuh,” katanya.
Demianus mengatakan Negara Indonesia terus menunjukan watak kolonial di hadapan dunia, karena tidak pernah menjalankan hukum yang dibuatnya sendiri dengan mengatasnamakan keamanan Negara. “Tidak akan pernah ada keadilan bagi kami, dengan kisah pilu yang [kami] alami. Mungkin Tuhan turun baru bisa ada jawaban bagi kami,” katanya.
Jimy Hilsom Hiluka—anak kandung mantan narapidana politik (Napol) Linus Hiluka yang dinyatakan bersalah terlibat peristiwa pembobolan gudang senjata Kodim 1702/Jayawijaya di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, pada 3 April 2003—memilih tidak ikut angkat senjata. Namun ia tidak menampik bahwa dirinya menyimpan harapan bahwa Papua akan merdeka.
Jimy masih berusia 16 tahun saat ia menyaksikan ayahnya ditangkap aparat kemanan. Ia juga melihat kakeknya meninggal ditembak aparat keamanan.
“Saya menyaksikan aparat keamanan menangkap bapak saya dan menembak kakek saya. Waktu itu bapak saya tidak lari ke hutan, [dan ditangkap] di rumah kami, di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, pada tanggal 27 Mei 2003,” katanya.
Setelah Linus Hiluka ditangkap, Jimy dan saudaranya kehilangan sosok ayah yang mengasuh mereka. Jimy kecewa karena Negara juga mengabaikan nasib mereka, tak memenuhi hak dasar mereka selaku korban konflik panjang di Papua.
“Waktu ayah saya ditangkap, saya sedih dan menyesal terhadap Negara Indonesia. Sebab, siapa yang mau memperhatikan kami? Masa depan kami seperti apa? Tapi Tuhan baik, sehingga kami semua bisa selesai kuliah,” katanya.
Jimy menyatakan seharusnya Negara memberikan perhatian kepara para anak tahanan politik atau narapidana politik, juga kepada para keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia serta pembunuhan di luar hukum yang dilakukan aparat keamanan, serta para korban konflik bersenjata yang berkepanjangan di Papua.
Dalam praktiknya, Jimy merasa Negara Indonesia seakan tidak menyadari bahwa anak-anak kombatan TPNPB sekalipun adalah warga negara dengan hak dasar yang harus dipenuhi Negara. Tidak pernah ada mengatakan bahwa, Negara tidak pernah memberikan restitusi, rehabilitasi, ataupun trauma healing bagi anak-anak TPNPB.
“Padahal Negara menghilangkan nyawa, atau mengamputasi hak asuh orangtua terhadap anak-anaknya. Meskipun orangtuanya ditahan, hak-hak korban itu harus diperhatikan oleh Negara. Apabila ada pembiaran seperti yang saya dan adik-adik saya alami, juga [pembiaran] kepada anak-anak korban pelanggaran HAM atau pembunuhan di luar hukum, itu bisa menjadi bumerang bagi NKRI,”katanya.
Jimy mengatakan Negara Indonesia seolah-olah memandang anak-anak kombatan TPNPB atau tokoh OPM maupun para korban pelanggaran HAM sebagai musuh. “Tapi saya sebagai anak-anak dari mantan tahanan politik dan anak pimpinan OPM, saya menyadari bahwa hal itu adalah sebuah konsekuensi yang harus diterima dan jalaninya,” katanya.
Bukan diwarisi, tapi mengalami
Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar yang banyak melakukan pembelaan hukum bagi tahanan politik maupun narapidana politik di Papua mengatakan hasrat untuk merdeka memang selalu ada di antara anak-anak kombatan TPNPB maupun tokoh OPM. Kombatan TPNPB kerap kali bergerilya dengan membawa serta anak mereka.
Di sisi lain, praktik kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan terus berulang. Di Papua, trauma atas konflik bukan cerita diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya, namun justru sesuatu yang dialami sendiri oleh Orang Asli Papua, dari generasi ke generasi.
“Pemahamannya bukan karena mereka diberitahu [orangtuanya] tentang konflik, melainkan mereka ikut terlibat dalam peristiwa tersebut. Mereka melihat bagaimana orangtua mereka melakukan perlawanan, bagaimana keluarga mereka menjadi korban. Jadi, internalisasi [hasrat untuk merdeka itu] karena pengalaman [sendiri], dan itu jauh lebih kuat [dibanding sekadar mendengar cerita orangtua],” katanya.
Menurut Siregar, pengalaman itu buruk dan menyakitkan, membuat anak-anak para tokoh TPNPB dan OPM kecewa, tapi juga membuat mereka marah. “Ada memori buruk yang ada di pikiran mereka. Akhirnya, setelah orangtuanya selesai berjuang, mereka merasa harus meneruskan perjuangan ayah mereka. Hal itu yang dialami Egianus Kogoya, Damianus Magai Yogi, dan anak-anak TPNPB/OPM lainnya,” katanya.
Siregar mengatakan bahwa hal serupa juga dialami anak-anak korban pelanggaran HAM, yang orangtuanya ditembak mati di luar hukum, dengan para pelaku yang tak kunjung diadili. Memori buruk tentang Indonesia pun terbentuk menjadi ingatan kolektif.
“Di kalangan anak-anak korban pelanggaran HAM juga terjadi internalisasi traumatik. Praktik impunitas [yang membiarkan pelaku tidak adili] itu semacam momok baru bagi orang Papua. Penderitaan yang dialami orangtua mereka itu bukan saja penderitaan mereka, tapi juga dia punya kelompok. Dia merasa itu menjadi keprihatinan bersama, apalagi Orang Asli Papua hidup dengan budaya komunal,” kata Siregar.
“Ketika melihat sejarah buruk terhadap orangtuanya, saudaranya, keluarganya, itu akan mereproduksi pemikiran untuk masa depan. Mereka melihat itu menjadi sesuatu kejahatan yang harus mereka perangi bersama.
Mereka tidak bisa melawan pada saat masih anak-anak, menyaksikan orangtua dan keluarganya dibunuh. Maka dia akan menyimpan kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan itu,” imbuh Siregar.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan hingga kini tidak ada kemajuan berarti atas kondisi dan situasi di Papua, khususnya dalam bidang HAM. Praktik kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu yang tidak kunjung diselesaikan, dan hal itu membuat orang Papua semakin melawan negara.
Yang terjadi saat ini, konflik bersenjata di Papua justru semakin meluas. Selain itu, para pihak yang bertikai, baik pasukan TNI/Polri maupun TPNPB, sama-sama abai terhadap norma hukum humaniter yang dibentuk untuk melindungi warga sipil pada situasi konflik.
“Dalam segi hukum humaniter, banyak sekali norma hukum humaniter yang tidak dipatuhi. baik itu oleh negara maupun oleh pihak berkonflik yang bersenjata dari Papua. Norma hukum humaniter misalnya, tidak boleh menyerang objek sipil atau sasaran sipil warga sipil, kantor pemerintahan sipil, rumah warga sipil. Kenyataannya justru itu terjadi. Norma lainnya, dalam berperang atau dalam konflik bersenjata serangan itu hanya bisa dilakukan terhadap objek militer atau sasaran militer, dan dilakukan secara proporsional. Itu tidak terpenuhi dalam banyak kasus,” kata Usman.
Usman menyatakan tidak ada proses penegakan hukum humaniter di Papua. Selain itu, tidak ada kebijakan resmi dari pemerintah yang menyatakan memberlakukan hukum humaniter di Papua.
“Dalam benturan konflik bersenjata, terdapat sejumlah kasus dimana ketika salah satu pihak tokoh pro kemerdekaam ditangkap masih mengalami penyiksaan. Penyerangan, penangkapan, dalam hukum humaniter hanya dibolehkan terhadap sasaran militer atau sasaran kepada pihak yang berperang,” kata Usman.
Usman mengatakan pendekatan keamanan tidak akan bisa menjadi solusi untuk mengakhiri konflik di Papua. Pemerintah seharusnya menempuh jalan non-kekerasan demi mencegah jatuhnya korban dari semua pihak, aparat keamanan maupun TPNPB, dan lebih penting lagi untuk mencegah jatuhnya korban dari pihak warga sipil.
“Jalan penegakan hukum lebih dikedepankan daripada jalan pendekatan keamanan yang mengandalkan pengarahan pasukan militer. Pengerahan pasukan militer hanya berujung dengan kekerasan yang merugikan semua pihak,” katanya.
Justru harus didekati
Kendati sejumlah anak tokoh TPNPB dan OPM merasakan pahitnya pengucilan dan diskriminasi, Kepala Kepolisian Daerah Papua (Kapolda) Papua, Irjen Mathius D Fakhiri justru menyatakan pemerintah tidak ingin mengucilkan mereka. Ia menyatakan anak-anak para tokoh TPNPB dan OPM adalah generasi baru yang berbeda dari orangtua mereka, dan tidak boleh didiskriminasi.
Ia menegaskan, di mana hukum anak tokoh TPNPB dan OPM memiliki kedudukan dan hak sama dengan warga negara lainnya. “Tanggung jawab kami, pemerintah, yang didalamnya ada Polri juga, untuk menjaga mereka menjadi warga negara. Saya melihat mereka sebagai masyarakat yang harus kita sentuh, kita layani. Mudah-mudahan dari mereka itu bisa menjadi duta pencerahan, pencerdasan bagi orangtua mereka atau keluarganya yang selalu berpikiran keluar dari Indonesia,” katanya.
Fakhiri mengatakan pemerintah justru ingin merangkul anak-anak anggota TPNPB atau OPM, dan bukan malah mengucilkannya. “Tidak pernah kami berpikir bahwa mereka masyarakat yang liar. Mereka malah harus saya dekati, supaya mereka bisa menarik saudaranya yang lain keluar dari paham yang mereka yakini, agar [mereka] menjadi warga negara yang baik. Saya memberikan contoh, ada keluarga mereka yang terlibat dalam KKB kami didik, saya tidak takut. Saya yakin dari mereka [ada yang] menjadi anggota Polri. Itu bisa menjadi stimulus, rangsangan bagi keluarganya untuk keluar [dari gerakan Papua merdeka] dan bergabung dengan negara Indonesia,” katanya.
Fakhiri menyatakan jajaran kepolisian akan memberikan perhatian khusus kepada mereka, agar mereka tidak terbawa arus. Menurutnya, anak-anak para tokoh TPNPB dan OPM justru menjadi jembatan komunikasi antara aparat keamanan dan TPNPB.
“Yang kami didik jumlahnya belum lebih dari 10 orang. Mereka dari daerah pegunungan, yang selama ini sedang [menjadi lokasi] kontak tembak. Mereka menjadi pengawasan khusus bagi kami, kami berharap mereka menjadi daya tarik tersendiri bagi keluarganya untuk meletakkan senjata dan kembali menjadi masyarakat normal,” katanya.
Fakhiri mengatakan menyatakan pihaknya justru tidak ingin mengucilkan para eks tokoh TPNPB dan OPM ataupun anak-anak mereka. “Mereka yang eks KKB tidak perlu lagi pantau. Namun sekali kali kami mengundang [mereka untuk] melihat perkembangannya setelah dia menjadi warga binaan. Kalau kami menjauhi, itu berbahaya. Kalau kami memberikan dia label, itu malah berbahaya. Biarkan mereka hidup bermasyarakat,” ujarnya.
Fakhiri mengatakan selama dirinya menjabat sebagai Kapolda Papua, tidak ada bagian atau kelompok masyarakat, termasuk anak-anak eks OPM, yang harus dimata-matai. “Kami malah membangun komunikasi, dengan begitu kita mengetahui apa kekurangannya, kebutuhannya, dan kemauannya,” katanya.
Bagaimanapun, sentimen anti Indonesia dan hasrat untuk memerdekakan Papua tetap hidup di kalangan generasi muda Orang Asli Papua, dan bahkah dihidupi oleh rangkaian panjang kekerasan baru yang terus terjadi Papua. Banyak pihak telah mengingatkan, banyak pihak juga menegaskan upaya pemerintah mengatasi masalah Papua tak menyentuh akar masalah Papua. Akankah kali ini pemerintah mau mendengar? (*)
News Desk